Nostalgi Sang Penyair Feminis: Pembicaraan Ringkas Dua Puisi Toeti Heraty
- Antinovel

- Dec 2, 2021
- 7 min read

Terjunlah dari tebing ini, di bawah sana lautan memori; album foto; kado ulang tahun ke lima; suasana kencan pertama; lagu yang mengingatkan pada mantan kekasih; atau apa pun yang membawa menuju masa lalu. Kejatuhan nostalgik itu tak akan merangum nyawa, tapi bersemogalah agar segala sesuatunya tak lagi mencekam. Terlebih, pada akhirnya kita pun akan menjadi bagian dari “masa lalu” itu sendiri.
Minimal, begitulah aku memaknai puisi Nostalgi = Transendensi karya Toeti Heraty itu. Aku tak perlu memastikan apakah operasi teks tersebut dimaksudkan demikian. Aku hanya ingin mengenang penyair yang sedang merayakan ulang tahunnya di sebuah negeri jauh di langit. Penyair cum pemikir feminis generasi pertama itu – seperti disematkan organisasi Satupena padanya, di mana ia menjadi salah satu anggota – lahir di Bandung, 27 November 1933.
Sekilas, tak ada sesuatu yang pelik untuk dipahami dari puisi tersebut. Kata-kata terjalin begitu ritmik. Tak ada peristiwa bahasa yang menjadikannya tampak gelap. Enjambemen yang membukanya sederhana: Nostalgi sama dengan transendensi/ betul, ini permainan kata. Ia memberikan pernyataan yang sekaligus dijelaskannya: hanya permainan kata-kata. Namun, bagaimana konklusi atas kerinduan itu disejajarkan dengan hal yang rohaniah, muskil dipahami, abstrak; sesuatu yang justru berada di luar segala kesanggupan manusia?
Mungkin saja karena kerinduan akan sesuatu yang jauh nun di seberang masa kini atau bahkan terhadap yang sudah tiada, sering kali hadir tak terkira sebagai sesuatu yang entah; tak terjelaskan. Tapi memangnya, adakah kerinduan bisa diduga atau direncanakan? Apakah kehilangan, perpisahan, atau semacamnya dimaksudkan untuk menciptakan kerinduan? Senarai pertanyaan itu tak terjawab, dan mungkin memang tak perlu dijawab penyairnya. Sebab ini permainan kata.
Lalu segeralah soal yang lainnya menyusul pada larik-larik kemudian ini: lagi-lagi kata asing/ tapi apa sih yang tidak asing. Adakah kerinduan yang sama dengan transendensi dan hanya permainan kata itu menempatkan kita pada kesadaran bahwa “asing” adalah sebuah niscaya? Mungkin iya.
Ibaratnya, sebuah gestur familiar saja cukup untuk mengundang kerinduan akan hal di masa silam. Saat berada dalam situasi tersebut, kita serasa asing karena hal familiar itu tak tersedia lagi di sini, pada masa kini. Berbagai keasingan selalu bersisian selama kita berada dalam waktu. Tapi ironisnya, nostalgia tak lebih dari sebatas rekoleksi memori, bukan suatu ritus resurjensi yang mampu memulangkan seseorang dari negeri arwah, misalnya, atau bisa tiba-tiba membuat mantan kekasihmu kembali. Syahdan, kita hanya terjebak dalam dalam ilusi; dengan sesuatu yang hanya khayali.
Kembali pada nostalgi/ berarti kehilangan/ yang dulu-dulu dibayangkan. Tri-baris selanjutnya itu lantas mengantarkan kita pada sebuah proses, sebut saja, penerimaan. Sebab mengingat masa silam berarti menyadari kehilangan atas hal-hal yang disangka akan abadi – atau setidaknya dapat bertahan sedikit lebih lama lagi – entah sebuah harapan, momen, atau perasaan. Terlebih, tak ada yang bisa kita duga kecuali ketidakterdugaan itu sendiri karena hidup, sebagaimana adanya ini, tak pernah memadai untuk sesuatu semacam itu. Dalam esainya bertajuk Amour de Vivre (1937), Albert Camus menulis, “Dunia tidak dibuat sesuai dengan selera dan keinginan manusia, melainkan untuk memerangkap manusia”. Ia terhenyak betapa orang-orang dengan begitu mudahnya merasa seolah mereka menemukan kepastian di dunia ini.
Tetapi kini kehilangan itu tidak mencekam lagi, karena/ lembut dengan ironi// Pada larik ini tampak sebuah kesan bahwa apa yang hilang di masa dulu, yang pernah membuat airmata berguguran di malam-malam musim sunyi, akhirnya hanya akan melebur dengan ironi.
Ini mungkin klise: mencintai, termasuk kecintaan pada hidup, selalu bersisian dengan konsekuensi-konsekuensi atas pilihan tersebut. Tapi kupikir ada benarnya. Bila ironi adalah bagian dari hidup, paling tidak aku mesti menerimanya dengan segala kerendahan hati. Maka alih-alih meratapi, aku akan menyusun apa-apa yang hilang dalam pusaran waktu tersebut pada etalase sebagai pengingat bahwa kita telah bertahan hingga masa kini.
Toeti lantas menutup puisi tersebut dengan serangkaian baris yang tak lagi mempersoalkan kerinduan, tetapi seruan untuk bermenung ria tentang kini-dulu-nanti. Ia menulis: saat kini yang berkilas balik/ siapa tahu nanti/ kini ‘dulu’ nanti, teratasi/ bukankah itu transendensi?//
Demikianlah catatan ringkas tentang puisi Nostalgi = Transendensi. Puisi yang menjadi tajuk antologi tersebut menjelaskan bahwa dunia Toeti memang dunia ide, seperti ia sampaikan sendiri dalam sebuah wawancara dengan Harian Kompas, 23 November 1994 silam.
Sebagai seorang penyair cum pengajar filsafat, ketangguhannya menyelami lautan minda begitu apik. Lirik-lirik kontemplatif tersebut barangkali menjadi semacam pembenaran bahwa “pertanyaan, barangkali adalah jawaban itu sendiri”.
Sosok Toeti di gelanggang kesusastraan Indonesia termasuk menonjol mengingat lebih sedikitnya perempuan penyair yang dikenal publik luas dibandingkan laki-laki penyair. Selain trajektori yang tak terlampau jelas – aku tak perlu menguraikannya sebab Saut Situmorang telah hatam membahas hal tersebut[1] – dominasi patriarkis menambah suram dunia sastra Indonesia.
Tapi pendiri Jurnal Perempuan itu melawannya lewat sebuah ledakan puitik bertajuk Post Scriptum.
Magasin Kata-kata Sang Penyair Feminis
Manakala sedang tak membahas dunia (dan) manusia, sebuah puisi kadang membicarakan dirinya sendiri. Itulah kredo kepenyairan tentang bagaimana kata-kata ditaruh dalam magasin sebelum akhirnya meledak menjadi sebuah lesatan puisi. Pada antologi Nostalgi = Transendensi, Toeti menuliskan hal semacam itu dengan tajuk Post Scriptum.
Kehadiran puisi tersebut kupikir begitu krusial di tengah simpul wacana yang didominasi maskulinitas. Entah dari sirkulasi, kuratorial, atau bahkan dari sejak penciptaan karya sastra itu sendiri. Bila keberadaannya bukan sebagai penonton (pembaca), maka perempuan tak lebih hanya objek gubahan seorang pesastra. Anggapan yang terakhir mungkin tak relevan – atau masih, entah. Namun, amatan Feby Indriani tentang ‘All Male Authors’ di Nominasi Penghargaan Sastra 2020 Badan Bahasa, membuktikan bahwa ada yang timpang dalam kesusastraan Indonesia[2]. Feby merincinya bahkan bukan pada masa penciptaan Post Scriptum milik Toeti Heraty di tahun 1995, tetapi tahun kemarin!
Bila Subagio Sastrowardoyo mengukur daya ledak puisi pada batas-batas ironi yang mengingatkan kepada langit dan mega, kisah dan keabadian, pisau dan tali, dan kepada bunuh diri, maka Toeti Heraty lain lagi. Dentum lirikal Post Scriptum ditujukan untuk – meminjam perkataan Gadis Arivia kala mengenang Toeti – merayakan tubuh dan seksualitas perempuan, cara berada dan berpikir perempuan. Toeti merakitnya dengan komposisi sebagai berikut: imajinasi yang liar, gerak tubuh yang bebas dan bahasa tanpa batas.
Ekspresivitas Toeti menyasar budaya tabu pembicaraan (penciptaan sajak) tentang ketubuhan perempuan dan seksualitasnya[3].Simaklah lima baris dalam bait pertama puisi tersebut: Ingin aku tulis/ sajak porno sehingga/ kata mentah tidak diubah/ jadi indah, pokoknya/ tidak perlu kiasan lagi//
Ledakan lirikal tersebut adalah upaya Toeti untuk mengebom operasi kuasa atas ekspresi seksualitas dalam penciptaan karya sastra. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa konstruksi kultural atas keadaan tersebut ditentang sang penyair. Ia berupaya mengetengahkan konsepsi hubungan seni dan masyarakat, budaya dan hak-hak dasar, dan kapasitas manusia untuk mengekspresikan diri secara bebas.
Silang kelindan antara realitas dan teks puisi tersebut memerikan pemahaman tentang bagaimana konvensi sosial, misalnya norma-norma seksual, tak pernah berubah. Dalam realitas sosial sering kali ditemui bahwa perempuan dan laku seksualitasnya merupakan sesuatu yang mesti ditutupi dan disembunyikan atas desakan sesosok monster bernama patriarki. Tetapi Post Scriptum berupaya menentangnya.
Bait tersebut lantas disusul oleh senarai analogi ini: misalnya payudara jadi bukit/ tubuh wanita = alam hangat/ senggama = pelukan yang paling akrab// Baginya, pengaburan tersebut menjadikan pengetahuan anatomi dan seksualitas menabu. Sebab, menyitir Ayunda Nurvitasari dalam laporannya di laman Magdalene, tidak adanya pendidikan akan hal tersebut turut berperan mengapa anak muda Indonesia belum sepenuhnya memahami konsep kepemilikan tubuh. Selain itu, masih dalam laporan yang sama, masyarakat tak berhak menentukan apa yang mesti dipakai atau bagaimana perempuan harusnya mengekspresikan diri[4].
Dalam kata lain, pandangan terbatas mengenai hal tersebut adalah sesuatu yang fatalistik. Sebab darinya, tubuh dan seksualitas perempuan, atau bahkan keutuhan eksistensinya, dipenuhi paradoks dan ironi yang menempatkan perempuan pada keterbatasan dalam mengekspresikan tubuhnya.
Pada puisi ini Toeti tak ingin berkenalan dengan eufemisme sebab mungkin memang tak ada yang mesti disembunyikan dalam komposisi eufimistik. Ia justru ingin mendobrak segala batas tentang apa-apa yang menelikung perempuan dan ekspresi seksualitasnya.
Maka dari itu, sang penyair tak ingin menciptakan sajak yang memosisikan perempuan sebagai objek subordinat. Tetapi mempertimbangkan segala eksistensi, kemerdekaan, dan kebebasan yang melekat terhadapnya. Sebab, meminjam perkataan Chimamanda Ngozi Adichie, “Yang bermasalah dengan gender adalah ia menentukan bagaimana kita seharusnya, bukan mengakui siapa kita sebenarnya. Bayangkan, betapa bahagianya kita dan seberapa bebas diri kita sebenarnya jika kita tidak memiliki bebas ekspektasi gender”.
Selaras dengan argumen tersebut, Toeti mengajak penikmat sastra untuk lebih memahami kebebasan atas tubuh kita sendiri. Dalam Post Scriptum, Toeti melukiskan potret perempuan dan seksualitasnya sekaligus berupaya meruntuhkan tembok raksasa yang dibangun di atas budaya patriarki itu; yang mengaburkan pandangan; yang telah merekonstruksi pikiran dan nalar masyarakat; sebuah tempat di mana segala hal tentang perempuan harus dikiaskan.
Bebaskan, seperti halnya Ursula Brangwen – karakter fiksi dari novel karangan D.H Lawrence – yang menari dengan telanjang di atas bukit. Dengan permisalan semacam itulah puisi ini ditulis; secara telanjang dan cerdas, tak menutupi apapun karena memang tidak perlu. Sebab dengan cara itu terlihatlah unsur eksistensial dalam memerankan diri sebagai individu yang memiliki akal dan pikiran untuk tak larut dalam legitimasi keliru tentang perempuan yang seolah rendah dan lemah.
Mengutip teori Jaques Lacan mengenai “aturan simbolis”, perempuan selalu menjadi “sesuatu yang lain” (the other). Dalam konstruksi sosial budaya yang dikemas oleh rasionalitas patriarki, perempuan berada pada posisi subordinat, dikenai beragam aturan, serta berbagai bentuk kontrol. Hal tersebut menempatkan perempuan sebagai si liyan. Maka titik itulah yang dibidik Toeti. Ia melesatkan penolakan terhadap simbolisasi ketubuhan [Payudara jadi bukit/ tubuh perempuan = alam yang hangat] yang hadir sebagai konter atas rasionalitas patriarkis tersebut. Dalam padangan ekofeminisme, tubuh perempuan dan alam menjadi satu kesatuan persamaan simbolik karena sama-sama ditindas oleh mereka (other) yang memakai atribut maskulinitas.
Tubuh adalah representasi tentang keberadaan manusia yang menandai suatu simpul utuh tentang eksistensinya. Bila mengungkap makna asali dari bagian tubuh perempuan dipandang sebagai sebuah dosa sehingga masyarakat/penyair enggan untuk merepresentasikannya sebagai kesatuan yang solid, apakah keberadaan perempuan pun harus dibiaskan?
Simaklah caturbaris ini: Yang sudah jelas/ tulis sajak itu/ antara menyingkap dan sembunyi/ antara munafik dan jati diri// Maka tampaklah bagaimana sang penyair berusaha keluar dari sebuah situasi batas; antara singkap-sembunyi, antara munafik-jati diri. Ia mungkin tak peduli betapa pun sajaknya dilabeli sajak porno tinimbang melahirkan hipokrisi. Sebab payudara, tubuh wanita, senggama adalah bagian dari perempuan yang tak perlu lagi repot disamarkan untuk menciptakan sebuah sajak yang estetik. Lagi pula sajak porno lebih baik ketimbang sajak yang melanggengkan dominasi patriarki!
Arkian, begitulah pembicaraan ringkas dua puisi Toeti Heraty yang termuat dalam antologi “Nostalgi = Transendensi”. Kini ia telah menjadi bagian dari masa lalu, tapi semogalah tulisan ini memadai sebagai sebuah reminisensi.
ANGGA | ULFA NURAENI
[1] Bacaan mengenai pandangan Saut dapat dijumpai pada tautan berikut: Penolakan Saut Situmorang Atas KLA.
[2] Feby Indriani, All Male Author’s di Nominasi Penghargaan Sastra 2020 Badan bahasa. Diakses dari Magdalene.co pada 14 November 2021 pukul 03.36 WIB.
[3] Nimas Diah Putri & Syaiful Qadar Basri, Konstruksi Gender Melalui Representasi Alam Dalam Puisi Post Scriptum Karya Toety Heraty Dan The Snake Charmer Karya Sarojini Naidu, dimuat dalam Haluan Sastra Budaya, Volume 2, No. 2 Desember 2018.
[4] Ayunda Nurvitasari, Tak ada Alasan Untuk Kekerasan: Otonomi Tubuh dan Relasi Kuasa dalam Pencegahan Pemerkosaan. Diakses dari laman Magdalene.co pada 14 November 2021 pukul 03.52 WIB.
Tulisan ini tayang pertama kali di laman jumpaonline.com





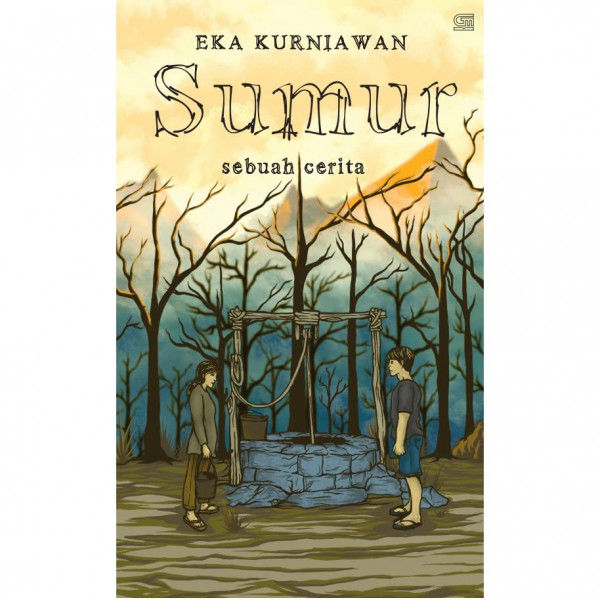
Comments