Selain Menanti Pecah: Tentang Puisi Chan Khun Ning
- Antinovel

- Nov 2, 2021
- 4 min read

Aku tahu, begitu malam berakhir, hidup akan berangsur-angsur menepi ke sebuah saat yang misterius. Segala sesuatunya tak pernah bisa kuduga eksepsi bahwa dua jam atau lima menit atau kapan pun setelah aku menuntaskan tulisan ini, akan ada penderitaan dan keputusasaan lain yang menanti dengan setia.
Aku pernah berada pada sebuah malam yang begitu sunyi, hanya sepi menjelma belukar di dalam kamar. Segala suara seperti terserap oleh suatu daya magnetik sehingga hanya menyisakan degup jantung. Jika musik mampu mendeskripsikan sebuah keadaan, maka itu adalah saat ketika aku menyimak picking Fjaer kala melantunkan “11 Days”. Sekilas aku merasakan suatu tanda yang hadir secara tiba-tiba, dan aku percaya kehadiran tersebut menyeruak dari keyakinanku bahwa tak ada yang istimewa dari semuanya ini.
Di tengah lanskap itu, aku semakin takut terhadap segala sesuatunya. Dalam hening aku sering kali bertanya, bagaimana bila nantinya aku yang pengecut ini tak sanggup menghadapi rentetan penderitaan yang saban hari diderakan oleh hidup ini? Adakalanya aku ingin gugur saja. Hujan di luar kini berhenti dan menyisakan genangan-genangan kecil di jalanan. Saat ini kupinjam puisi Yulden Erwin: “Kenangan ini menggigil dalam angin. Di sini, kepedihan tanpa kata”.
Seperti sesiapa yang berada di dunia, aku mengalami banyak derita. Penderitaan, apapun motifnya, kupikir bukan sekedar perasaan subjektif atau respons emosional tentang hal-hal tak menyenangkan, melainkan sesuatu yang bersifat kodrati; konsekuensi mutlak atau bahkan kutukan bagi yang hidup.
Di belahan geografis yang lain, Chan Khun Ning pernah merangkum fenomena tersebut lewat sebuah puisi bertajuk Balada Sebuah Derita yang dihimpun Jeniri Amir dalam Puisi-puisi Kenyalang II pada 1987. Aku tak akan membahas komposisi puitik atau soal-soal sastrawi lainnya dalam sajak penyair Malaysia itu. Aku bukan seseorang yang fasih membicarakan hal tersebut. Aku menulis untuk mencintai diriku sendiri sebab para penyair telah pergi di malam paling sunyi setelah membakar puisi-puisi yang tak pernah selesai itu.
Simaklah salinannya:
Perjalanan/ dari rahim ibu/ ke kuburan/ adalah buih/ di dada samudera/ yang/ ditampar angin/ dikeret arus/ digoncang ombak/ tersingkir ke pantai/ menanti pecah//
Dalam puisi tersebut, mungkin samudera adalah ruang yang kita tinggali, ruang yang disebut Edouard Jeanneret sebagai bukti akan keberadaan. Sementara perjalanan menuju pecah adalah waktu. Dan kita cuma bisa menunggu: atau di dalam sajaknya Subagio Sastrowardoyo bertitah untuk lari sebelum semuanya berakhir, semuanya luput.
“Perjalanan” dalam puisi tersebut bisa diidentifikasikan kepada hidup manusia sebab ia memberi beberapa penanda seperti “rahim ibu” dan “kuburan” yang pembicaraannya tak bisa dilepaskan dari kelahiran dan kematian. Namun, jika puisi adalah interpretasi yang merefleksikan pandangan penyair terhadap kehidupan, mengapa Khun Ning begitu putus asa mendeskripsikannya? Seakan tak ada ruang bagi kebahagiaan barang sebaris kalimat atau sepenggal kata pun. Ia mungkin menuliskannya dengan segala cemas yang mengambang di langit-langit rendah kamarnya, dengan kerinduan tentang sorga yang hilang, tentang rahim ibunda yang tak mungkin kembali dimasuki meski kaosnya dunia membikin tangis tak henti-henti.
***
Langit di luar mungkin begitu kosong, tanpa bintang-bintang yang bertabur atau rembulan yang pernah membuatku jatuh cinta serta berharap agar semuanya tak segera berakhir. Aku tahu harapan itu terdengar seperti omong kosong, aku tak akan bisa mengekalkan malam tersebut. Tapi itulah cintaku, cinta yang sunyi untuk hal yang tak mungkin kumiliki.
Ni Made Purnama Sari boleh saja berkilah bahwa “akhirnya kita akan abadi”, tetapi untuk merengkuh itu, pertama-tama aku mesti melalui jalan terjal “masa kini”. Dan bila perjalanan tersebut adalah laut yang kalut, satu gestur saja cukup untuk memecah buih sepertiku. Sesuatu yang buruk bisa saja terjadi dan aku pasti akan sesegera mungkin untuk tiada.
Suatu hari di tahun 1937, Albert Camus pernah menulis sebuah esai bertajuk Amour de Vivre. Ia mengatakan bahwa, “Satu hal yang membuat perjalanan jadi berarti adalah rasa takut”. Aku bersepakat sebab mungkin saja perasaan tersebut hadir dari keyakinan bahwa samudra adalah hamparan bagi setiap ancaman. Terlebih, perjalanan yang digambarkan Khun Ning adalah perjalanan yang merangum segala kenyamanan, suatu ide yang berkutat pada konsep penderitaan.
Itu adalah sebuah safari yang tak pernah diimpikan siapa pun, kupikir. Sebab kegetiran yang datang secara sporadik tersebut tak didesain sesuai dengan prototipe manusia. Ia menuliskannya dengan sesuatu yang lirih-perih, laiknya seseorang yang telah bersiap untuk gugur pada hening malam. Menghadapi ancaman maut barangkali memang terasa heroik, namun pada saat yang nyaris bersamaan, ironi dan tragedi senantiasa membayang. Ketiadaan harapan membikin suasana dalam puisi tersebut monokromatik, tampak begitu kelam, menyakitkan, dan seakan tak pernah mungkin terhindarkan.
Tapi bila penderitaan nyalar ada sepanjang manusia berhadapan dengan kesadaran, mengapa tak ada pilihan yang disodorkan selain keputusasaan? Aku ingin melawannya karena aku percaya pada diriku meski tahu bahwa hidup adalah palagan yang tak akan pernah dimenangkan oleh seorang pun. Bila hidup seumpama laut yang kalut, aku akan meleburkan diri kepada ombak ketimbang menanti pecah di pantai. Atau aku akan menjadi bagian dari pendar kemerahan di permukaan hangat laut kala metari hampir terbenam, sementara sepasang kekasih memandanginya sambil bertanya apa yang telah mereka lakukan sehingga berhak mendapatkan kebahagiaan semacam itu. Aku ingin menjadi apa pun asal bukan keputusasaan.
Aku percaya bahwa aku tak keliru. Aku tak mungkin berserah sepenuhnya. Sebab bila itu terjadi, lantas bagaimana aku bisa benar-benar hidup? Aku ingin segalanya terus berjalan meski diiringi perasaan khawatir bahwa suatu hari, entah kapan, semua ini akan berakhir.
Setelah hari-hari yang sulit ini berlalu, aku tahu aku akan hilang, terlupakan. Aku tak akan lagi punya kesempatan untuk semata menyeruput kopi atau meminum Intisari pada tiap sore yang suam di bawah langit sendu dan haru, dalam semburat kemerahan yang pudar perlahan dan tergantikan cahaya ungu sebelum gelap menjadi penuh. Maka selama masih terjaga, aku akan menghabiskan waktu untuk mencintai segalanya dengan cinta yang tetap rahasia, tak terkatakan, yang kelak melenyapkanku.
Aku tak ingin hanya menanti pecah. Bila hidup adalah laut yang kalut, aku akan melebur menjadi ombak atau pendar kemerahan di permukaan air yang dipandangi sepasang kekasih di ujung teluk sambil membayangkan semuanya ini tak pernah berakhir. Maka kini dan di sini, kupinjam larik puisi Ni Made Purnama Sari yang lainnya: “Telah engkau lepaskan aku dari tubuhmu/ kau biarkan aku berjalan ke daratan tak bernama itu”.
Bandung, 2 November 2021




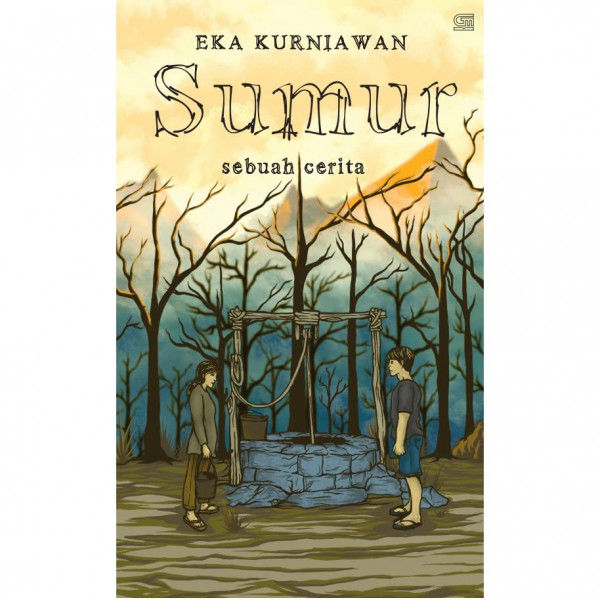

Comments