Tentang Kritik Sastra: Sebuah Surat Pembaca
- Antinovel

- Mar 3, 2022
- 8 min read

– Tanggapan atas rubrik Ahwal dalam Buletin Sarasa Edisi 4, 28 Februari 2022
I
Redaksi Buletin Sarasa yang terhormat, saya memberanikan diri menulis surat ini setelah membaca edaran RUAS bahwa mahasiswa boleh berkomentar banyak hal, dan semoga pembicaraan terhadap buletin ini termasuk di dalamnya. Akan tetapi, saya perlu meminta maaf terlebih dahulu karena saya bukan pembaca yang tekun dan baik. Saya tidak membaca kesemua edisinya, juga tak menantikan tanggal terbitnya. Saya membaca hanya bila seorang kawan – mantan Pemred buletin ini – Fio Febriansyah yang saya hormati, membagikannya pada saya.
Tapi sedemikian itu, izinkanlah saya menyampaikan beberapa keluhan dan sedikit saran meski saya pun tak tahu apakah komentar ini akan bermanfaat walau hanya bagi sepasang kupu-kupu yang terjebak di kaca jendela kamar atau bagi seorang homeless yang tengah menahan lapar. Dengan penuh pengharapan, semoga dewan redaksi sudi membaca celotehan saya ini.
Begini: saya agak risau usai membaca Buletin Sarasa edisi 4 yang terbit pada 28 Februari 2022 lalu. Dalam salah satu rubriknya, saya menjumpai sebuah pertanyaan yang menyamar jadi tajuk tulisan itu: Pentingkah Kritik untuk Sastra?
Sejujurnya saya tak peduli dengan dua dari empat paragrafnya yang sebatas salinan[1] buku ajar Jendela Kritik Sastra. Jadi, bukan itu yang hendak saya bicarakan. Meski tentu saja saya menilai salin-tempel macam demikian bukanlah sebuah kebijaksanaan, betapa pun di akhir sang penulis menyebut judul buku tersebut sebagai rujukan.
Ada pun yang ingin saya sampaikan adalah: saya terkenang pada esai Saut Situmorang yang terbit sepuluh tahun silam. Dalam esai-dua belas lembar kertas A4 kuarto yang terbit di blog boemipoetra[2] tersebut ia menyelisik rimba kesusastraan kita yang begitu sunyi tanpa kehadiran kritik(us) sastra. Sebab sepeninggal Jassin, Teeuw, Subagio, studi kritis terhadap karya sastra tak pernah benar-benar dilakukan. Kalau pun ada, konon hanya sebatas apresiasi atau komentar asertif belaka. Hal ini tentu ironik karena kritik, bagaimana pun, adalah semacam pasangan hidup bagi karya seni sastra supaya tidak hidup kesepian, halusinatif dan kering meranggas[3].
Maka, sewaktu berjumpa dengan tajuk Pentingkah Kritik untuk Sastra? dan empat paragraf isinya, justru hadir pertanyaan lain: seberapa penting membicarakan “penting atau tidaknya kritik bagi susastra”? Bukankah sudah jelas penting? Sementara di sisi yang lain, persoalan utamanya bahkan baru hadir pada dua alinea terakhir. Saya jadi mikir, yang perlu dijadikan pertanyaan justru bukan pentingkah kritik untuk sastra, tetapi pentingkah tulisan tersebut dimuat di media mahasiswa sekaliber HMBSI? Bukan apa, selain tak ada pertautan antara isi dan tajuknya, pembahasan yang coba diketengahkan pun rumpang.
Bila artikel tersebut ditujukan untuk merinci “apa itu kritik sastra” mungkin sah-sah saja, meski Alwi Atma Ardhana pernah bilang pertanyaan demikian konon terlalu berat untuk dijawab dan kalau pun ada jawabannya, cenderung tak memuaskan – dengan sepenuh kesadaran saya menyepakatinya. Sebab, kabarnya krisis yang melanda sastra kita sejak zaman Balai Pustaka, sampai polemik cybersastra pada 2002 hanya satu dan masih berlangsung hingga hari ini; yakni krisis kritik(us) sastra. Pendapat Alwi tersebut yakni didasarkan pada makalah Budi Dharma yang dipaparkan dalam gelaran Temu Sastrawan III di Tanjungpinang, dua belas tahun silam: “Semua pendapat mengenai sastra pada hakikatnya adalah kritik sastra”[4]. Pernyataan demikian tentu saja merupakan simbol parahnya nasib sastra kita. Sebab bagaimana mungkin misalnya, sebuah blurb yang ada di sampul belakang novel-novel disebut kritik sastra, meski kehadirannya merupakan pendapat mengenai karya sastra?
Kecenderungan generalisasi pemakaian term kritik sastra juga ditemui dalam artikel yang ditulis Lismawati. Ia menulis, “Kritik sastra tidak selalu benar. Bahkan sering salah. Hal itu diakibatkan karena kritikus sering tidak menyadari perasaan pengarang ketika menulis”. Klaim tersebut bukan hanya tak memuaskan, tapi sudah harus gugur sebelum ditulis. Sebab bila dipertahankan, bukan tak mungkin kritik yang dimaksud hanyalah sebuah pseudo-analisis atas karya-karya sastra.
Masalah perasaan dan semacamnya yang dipandang sebagai manifestasi dari kehidupan psikis pengarang dalam kajian sastra adalah persoalan lain yang pada konteks tulisan ini bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan pembahasan interdisipliner yang mempertemukan antara ilmu sastra dan psikologi[5]. Tanpa konsep dan kerangka teori psikologi, pembicaraan tentangnya tak akan menemui kesepahaman. Bahkan, sebelum menuju persoalan tersebut, ihwal “siapa kritikus sastra” pun juga memiliki polemiknya sendiri. Acep Iwan Saidi pernah memaparkannya 22 tahun lalu dalam Jurnal Wacana Vol. 2 Nomor 1, April 2000[6] – meski mungkin tak lagi relevan, entah.
Terkait soal terakhir di atas, setidaknya Lismawati mesti menjelaskan “siapa kritikus sastra” agar ia tak hanya menggantungkan argumen pada “kehati-hatian” dan “kemampuan diri sendiri”. Sebab, pernyataan tersebut jelas tak mengandung implikasi nilai kritik sastra. Profesi kritikus didasarkan pada tanggung jawab keilmuan di mana dua hal yang disebutkan hadir sebagai suatu konsekuensi logis. Dalam kata lain, sudah semestinya seorang kritikus melakukan segala pertimbangan teoritis yang disusun secara metodik atas dasar pendekatan tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tapi, artikel dalam buletin tersebut luput membicarakan kriteria bagi seseorang untuk berhak disebut sebagai kritikus yang mengharuskan adanya penguasaan keahlian khusus/pengetahuan komprehensif atas sebuah genre sastra, serta sebuah sikap “profesional dan kritis”. Padahal jelas bahwa posisi seseorang sebagai kritikus menuntut “penilaiannya” terhadap karya sastra dilakukan menurut etika kritik yang berlaku universal – kritis, adil, dan jujur – tidak bergantung pada impresi subjektif apa lagi sentimen tak berdasar semata.
II
Sebab yang dibicarakan adalah penelaahan (kritik), maka sastra perlu ditempatkan sebagai sebuah objek kajian; karya seni yang mediumnya adalah bahasa. Tapi bukan berarti penafsiran terhadapnya “sulit diterapkan dalam metode keilmuan” seperti yang tertulis dalam buletin edisi tersebut. Bila demikian lantas apa gunanya ilmu sastra yang diazamkan untuk mempelajari teks sastra serta gejala yang menyertainya – peristiwa dan fakta-fakta sosial yang berkaitan dengan keberadaan karya, pengarang, pembaca, lembaga penerbitan, media massa, dan sebagainya?
Hal inilah yang dirisaukan Saut Situmorang dalam esainya yang lain, Sastraku Sayang, Sastraku Malang. Ia mendedah nasib tragis sastra kita yang kadung dianggap hanya sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hati dan perasaan belaka. Padahal, diperlukan seperangkat ilmu dalam pembicaraan dan penafsiran terhadapnya.
Sekaitan hal itu, sudah seharusnya Buletin Sarasa sebagai corong media himpunan mahasiswa jurusan Sastra di mana anggota redaksinya adalah sesiapa yang “paham” dengan kesusastraan bisa memutus nasib tragis tersebut. Lismawati mestinya mampu mendasarkan argumennya pada sastra sebagai cabang ilmu pengetahuan; sebagaimana kita mempelajarinya pada ruang kuliah, seperti orang-orang menempuh studi kedokteran, arsitektur, linguistik, dan lainnya[7]. Dengan demikian kita tak lagi meninjau sastra sebagai soal-soal perasaan, melainkan menempatkannya sebagai sebuah studi sistematik dan karenanya dibutuhkan perangkat analitik untuk melakukan pembedahan terhadapnya.
Memang, sastra dan ilmu sastra adalah dua hal berbeda. Tapi, bukankah ironis bila seorang mahasiswa Sastra menulis di media himpunannya bahwa sastra “sulit diterapkan untuk metode keilmuan”? Padahal, di semester awal pun kita telah dikenalkan dengan studi sistematis atas historisitas, teori, serta jenis karya sastra di mana hal tersebut didasarkan pada keilmuan yang sistemik. Memang pula kritik sastra sendiri lahir sebagai ekspresi personal dari proses pembacaan sebuah karya. Akan tetapi, tiap pembicaraan yang berhak disebut sebagai sebuah “kritik sastra” mestilah memiliki seperangkat “teori” analisis, interpretasi dan evaluasi yang berlaku universal. Atau meminjam perkataan Saut, “Sebuah ‘kritik sastra’ tidak bisa dilakukan hanya tergantung pada kata hati belaka!”
Bagaimana mungkin sebuah proses “penyampaian kembali”, seperti yang ditulis dalam buletin tersebut, dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa kaidah-kaidah yang jelas, tanpa penerapan teori sastra, tanpa analisis interpretatif nan evaluatif? Padahal, bukankah kehadiran hal-hal itu punya arti penting dalam kritik sastra biar analisisnya tak terjebak emosionalisme semata? Bagaimana mungkin kita akan memercayai “penyampaian kembali” yang dilakukan tanpa lebih dulu melalui proses textual study dan keseriusan semacamnya secara menyeluruh atas sebuah karya sastra? Bukankah itu sama saja seperti kita memercayai klenik sebagai sesuatu yang masuk akal padahal justru sebaliknya?
Bila kritik “tidak selalu benar” – meski di bagian lain dikatakan bahwa kehadirannya jangan dinafikan – hanya karena kritikus sering kali tak mengindahkan perasaan pengarang, maka studi sastra adalah kesia-siaan. Maksud saya, untuk apa fakultas dan jurusan-jurusan sastra dibentuk bila yang akhirnya dituntutkan kepada kritikus adalah emosionalisme, soal-soal perasaan? Mereduksi istilah kritik(us) sastra sama saja dengan mempertontonkan minimnya pengetahuan kita yang saban hari bercinta dengan sastra. Sebab bagaimana pun, kritik sastra disusun dengan spirit intelektual dan tanggung jawab terhadap kesusastraan
III
Tetapi, sejujurnya saya pun mafhum. Barangkali, keterbatasan ruang dalam buletin tersebutlah yang membikin persoalan sepelik kritik sastra tidak terjelaskan secara komprehensif. Enam pagina yang dibagi menjadi empat rubrik, termasuk halaman judul, susunan keredaksian, serta daftar isinya, saya kira tak akan cukup memadai. Maka dengan segenap hormat, perkenankan saya menulis kalimat ini: sudah selayaknya Buletin Sarasa lebih progresif dari segi diskursifnya, yang tentu dibarengi dengan penambahan jumlah halaman. Entah untuk esai-esai, berita menyoal kegiatan sastra, juga bagi ruang berkarya mahasiswa berikut apresiasi terhadapnya. Kolom-kolom yang sempit itu mesti diperluas.
Apakah harapan saya tampak deksura? Mungkin. Memangnya saya siapa? Apakah maksud harapan tersebut agar karya saya dimuat di sana? Mungkin juga. Namun, sesungguhnya, saya amat rindu membicarakan pemikiran menyoal sastra sambil memandangi rembulan dengan beberapa kawan yang salah satunya saya harapkan bisa ditimba dari Buletin Sarasa.
Saya tak menuntut Dewan Redaksi untuk melakukan revisi terhadap edisi tersebut atau sekedar menerbitkan surat pembaca ini. Siapalah saya. Saya menyusun tulisan ini hanya karena merasa saya mencintai Sastra. Saya tak merelakan kekasih saya tersebut dibicarakan dengan tidak semestinya. Saya tak akan menuliskan puluhan paragraf ini hanya untuk menanggapi empat alinea – yang dua di antaranya hanya salinan semata – bila bukan karena saya mencintai sastra dan menginginkan diskursus tentangnya selain dalam ruang perkuliahan. Maafkan saya bila ada bagian dalam tulisan ini yang melukai.
Sebagai epilog, perkenankan saya menyusun ulang perkataan Polanco Surya Achri: “Saya merasa kesepian, merasa orang-orang semakin asing. Sastra menemani saya meski sering juga muncul pertanyaan, ‘Siapa yang membutuhkan sastra?’”
Kadang, saya yang murung, soliter, dan pemalu ini tak memiliki kepercayaan selain kepada sastra.
Bandung, 2 Maret 2022
Angga Permana Saputra
______________
Catatan akhir: [1] Lihat Ambarini & Nazla, Jendela Kritik Sastra (Semarang: UPGRIS, 2016), hal. 1-2.
[2] Blog boemipoetra merupakan versi online dari jurnal sastra independen dengan nama yang sama. Diasuh oleh penyair, esais, dan kritikus sastra Saut Situmorang.
[3] Saut Situmorang, Dicari Kritik(us) Sastra, dimuat dalam blog boemipoetra, 20 September 2012.
[4] Alwi Atma Ardhana, Apa Itu Kritik Sastra, dimuat dalam blog boemipoetra, 13 Mei 2013. Melalui pemaparannya, ia menjelaskan historisitas istilah dan perkembangan konsep kritik sastra yang sebagai hasilnya terciptalah (beragam) tradisi sastra.
[5] Wiyatmi, Psikologi Sastra: Teori dan Aplikasinya (Yogyakarta: Kanwa, 2011), hal. 20.
[6] Acep Iwan Saidi, Kritik Sastra: Pokok-Soal yang Tak Kunjung Tercerahkan, dimuat dalam Jurnal Wacana Vol. 2 Nomor 1, April 2000, hal. 121-123. Ia menyelisik bagaimana iklim kritik sastra (saat itu) yang berada di bawah bayang-bayang keagungan sang Paus Sastra H.B. Jassin. Usai Jassin wafat, khazanah kritik sastra dinilainya mengalami stagnasi. Hal tersebut tak lain adalah riak dari melegendanya Jassin sehingga bagian tragisnya, generasi kritikus setelahnya didera penyakit akut: yang sering muncul justru bukan kritik, melainkan perdebatan menjenuhkan yang berputar pada lingkup itu-itu saja, yakni kurangnya kritikus yang berwibawa, tak sejalannya pandangan kritikus dengan sastrawan, kritik yang meninggalkan teks, metodologi yang kedodoran, kritik yang tak membumi, dan pertentangan antara kritik akademis dan nonakademis. Dalam artikel tersebut, Acep menawarkan alternatif tentang polemik ini: memfungsikan Sarjana Sastra sebagai kritikus yang intens menerbitkan kritiknya di media massa. Hal ini tentu bertalian dengan bagaimana mutu pendidikan sastra di universitas. Meneruskan pernyataan tentang kelimbungan saya terhadap relevansi esai akademis Acep: saat ini telah bermunculan rubrik-rubrik penelaahan atas karya sastra di media massa. Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta bahkan telah menerbitkan situs kritik sastranya sendiri, yakni Tengara.id.
[7] Saut Situmorang, Sastraku Sayang, Sastraku Malang, dimuat dalam blog boemipoetra, 6 Desember 2017. Dalam esai tersebut Saut mula-mula bertanya tentang kesedaran kita terhadap sastra sebagai ilmu pengetahuan (science, sains) yang untuk memahaminya diperlukan sebuah studi sistematis. Tapi sebab sastra kadung dianggap sebagai soal-soal perasaan, maka hadirlah tragedi dalam khazanah sastra kita. Tragedi tersebut yang kemudian menjadi titik tolak dari pokok esainya. Ia menampilkan skandal-skandal yang dilakukan parasit-parasit yang cuma menumpang dalam gerbong sastra Indonesia. Salah duanya Saut mengangkat polemik Narudin Pituin yang kembali membuat klaim superlatif atas buku bertajuk Membawa Puisi Ke Tengah Gelanggang: Jejak dan Karya Denny J.A (2017). Buku tersebut tak lain adalah narsisme Denny JA dan umatnya. Selain itu, ia mengungkit Sutardji Calzoum Bachri dengan circle Majalah Horison-nya (Sapardi Djoko Damono, Leon Agusta) yang juga membaptis puisi esai sebagai benar-benar puisi.




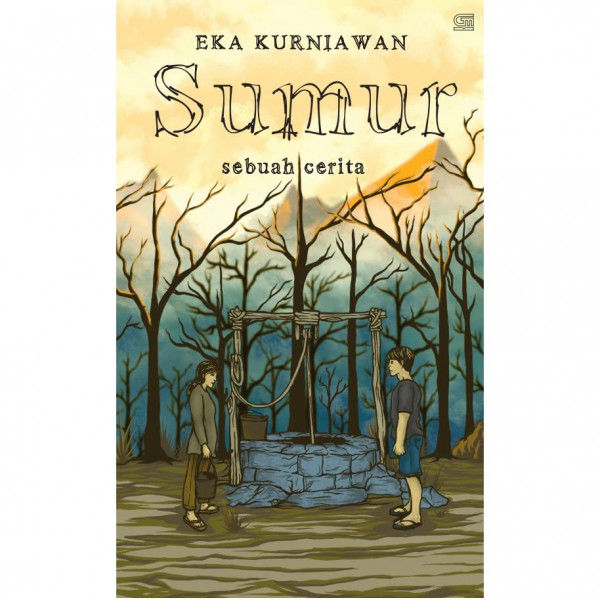

Comments