Poetry Therapy: Percaya Pada Puisi
- Antinovel

- Nov 8, 2021
- 4 min read

berdirilah di ruang tengah
rumah dunia terbakar ini;
biarkan tubuhmu jadi air
mancur di sana.
atau maafkan semua
kekacauan ini; pertempuran
& musim api masih akan
panjang.
– Aan Mansyur[1]
Aku percaya, di saat seperti ini, di mana hari-hari adalah kesedihan, puisi semacam itu menjadi sosok paling pengertian ketika tak ada seseorang yang mungkin akan mengerti tentang perasaanku. Sebab aku pun tak punya cukup kata untuk menjelaskannya. Maksudku, tanpa puisi sulit rasanya membayangkan bagaimana aku akan melewati hari-hari yang putus asa ini.
Tiap kali malam turun di kamarku dan sunyi mulai merambati tembok, kenangan nyaris mengisi segala ruang; di sela tumpukan pakaian, pada gelas bekas kopi, di atas lemari, dalam kepalaku. Semuanya berserak tak teratur, di mana-mana. Kesedihan tak terbendung. Dan itu membuatku putus asa. Segala sesuatunya hadir sebagai siksaan yang tak tertahankan serta tertampil dalam lanskap yang pesimistik.
Aku tahu perasaan tersebut hadir dari ingatan ketika bel perpisahan dengan yang terkasih dibunyikan dan cinta tak pernah cukup untuk membuatnya bertahan. Masih senantiasa kuingat bagaimana sebuah perasaan bahagia merimbuni benak dan dadaku pada perjumpaan pertama kami. Itu adalah sore yang mendung pada sebuah halte bus di kota Bandung. Tapi berbulan kemudian segalanya gugur saja tiba-tiba. Pedih diam-diam menjalar pada tubuhku begitu detik berjatuhan dari jam dinding di sekitar kejadian itu. Aku tak pernah mengerti mengapa peristiwa tersebut terjadi. Dunia memang tak kiamat. Namun itulah bagian paling menyakitkannya: waktu terus saja bergulir padahal aku ingin mati saat itu juga.
Adakalanya beberapa peristiwa adalah ingatan yang sedih-lirih untuk dikenang. Atau, meminjam perkataan Fauzi Sukri, ia menjadi semacam “Pertanda melankolia. Terkadang ia mendesirkan aroma daun teh yang segar; sesekali menggelegakkan getir udara laut di lepas pantai; bisa menjadi sebentuk rasa yang begitu kuat menautkan masa lalu dan masa kini tanpa begitu jelas beda keduanya”[2].
Pada sebuah sesi konseling, aku memercayai perkataan psikologku dengan segala kepercayaan yang diberikan Jan Olav kepada Veronika saat perjumpaan pertama mereka di sebuah trem di kota Oslo: bahwa kita tak akan bisa melupakan seseorang atau sebuah kejadian. Kita tak mungkin tiba-tiba amnesia – terlebih bila seseorang atau peristiwa tersebut memberikan pengaruh yang signifikan bagi hidup kita. Kita perlahan cuma bisa menerimanya sebagai suatu keharusan.
Sekarang aku mengerti kenapa aku terbayang sepasang mata Dewi Mnemosyne. Ia menganugerahkan memori yang memungkinkan manusia mengingat kembali masa lalu untuk mengerti apa yang terjadi sekarang dengan perspektif yang lebih jernih.
Ingatan dan kejadian selalu menjadi bagian dari waktu. Laksmi Wardhani menyebutnya bukan sebagai fenomena psikis semata, melainkan melibatkan struktur-struktur “ada” manusia sehingga bersifat eksistensial. Dan darinya aku bertemu “aku saat ini”.
Kini dan di sinilah aku bertahan.
***
Dalam mitologi Yunani, Asclepius, Dewa Penyembuhan, adalah putra dari Apollo, Sang Penyair. Itu setidaknya menjelaskan bagaimana karya sastra bisa diperhitungkan sebagai sarana kuratif. Puisi adalah ayah dari kesembuhan. Tanpa puisi sulit rasanya membayangkan bagaimana aku akan melewati hari-hari yang putus asa ini.
Aku pernah menjumpai sebuah puisi yang – meminjam larik Subagio Sastrowardoyo – mengingatkan aku kepada langit dan mega. Mengingatkan kepada kisah dan keabadian. Melupakan aku kepada pisau dan tali. Melupakan kepada bunuh diri[3]. Salah satunya adalah Self Help Poem milik Aan Mansyur yang kucuplik pada mukadimah tulisan ini. Puisi adalah sebuah dunia yang memadai bagi pergulatan batin manusia dan di dalamnya aku memiliki ruang untuk mengenali diri sendiri yang bahkan telah lama hilang.
Aku yakin bahwa puisi mampu menjadi salah satu medium dalam penyembuhan luka batin dan tanpa tahu mengapa suatu malam di linimasa Twitter, aku menemukan bahwa ada istilah untuk itu: poetry therapy, atau sering kali digantikan dengan biblioterapi demi mewadahi genre sastra secara lebih luas.
Poetry Therapy berpusat bukan pada teks puisinya[4], tetapi menyelisik riak yang timbul atas proses pembacaan atau penciptaan teks puisi itu sendiri, dari penghayatan subjektif. Konseli tak mesti menelaah komposisi puitik, atau unsur estetik, atau persoalan sastrawi lainnya. Secara mendasar, proses terapeutik dari metode yang secara historis digunakan sejak awal 19 tersebut adalah membaca, mengidentifikasi perasaan, memahami dinamika, serta eksplorasi diri.
Puisi menjadi semacam manifestasi dari kehidupan psikis manusia[5], suatu katalisator atas emosi yang hadir-menyeruak dan terkadang tak mampu untuk dijelaskan dengan cara apa pun. Aku selalu percaya, apa pun motifnya, sebagian orang tak mudah menyalurkan ekspresi dengan baik dan hal tersebut sering kali berujung sebagai dasar tindakan agresif dan destruktif, yang pada titik ekstremnya adalah self-destruction atau bahkan bunuh diri.
Memang, puisi tak memberikan efek yang sama bagi setiap orang. Tetapi – tanpa maksud mereduksi persoalan – seseorang yang terlibat secara intensif dengan sebuah puisi, akan mengenali, merefleksikan, lantas memetik aspek emosionalitas yang dimunculkan oleh suatu karya.
Dalam puisi, aku menjelajahi perasaan dan memberikannya sebuah bentuk simbolisasi lantas berusaha mencari resolusi atas konflik batiniah tersebut. Di sanalah aku melakukan perjumpaan dengan apa yang semula tak kuketahui tentang diriku sendiri. Sebab puisi, atau secara luas sastra, menyajikan kebenaran. Kebenaran yang tak diakui, kebenaran yang direpresi. Aku yakin puisi sebagai sarana simbolik adalah sebuah ruang di mana kita bisa menyusun dengan teratur, membangun sintesis, dan membentuk repesentasi diri (perasaan). Lewat pembacaan, juga penciptaannya, seseorang dapat menempatkan rasa sakit dan derita ke dalam sudut pandang tertentu untuk memaknai serta kemudian pulih darinya.
Saat aku menyusuri bait demi bait sajak Terimakasih Kepada Pagi milik Subagio Sastrowardoyo, setiap hal menjelma simbol rasa syukur yang merefleksikan hidupku. Penyair yang dikenang Dian Sastrowardoyo sebagai seseorang yang nyaman membicarakan hal sedih itu, justru memberikan gambaran atas harapan yang selama berbulan-bulan tak pernah kutemui. Ketika aku sadar betapa berharganya hidup, aku lebih menikmati momen-momen di dalamnya. Dalam hidupku, rasanya tak ada tempat yang memberikan efek pengasingan ataupun pendekatan terhadap diriku sendiri selain pada puisi.
Menjumpai metafora dalam puisi membantu memahami realitas yang kuhadapi. Pemahaman tersebut mungkin saja hadir secara reaktif dan bahkan irasional. Tetapi darinya aku bisa mengambil jarak dengan diri sehingga memiliki pandangan yang lebih objektif dan aku punya ruang untuk terlibat dalam dialog dengan diriku sendiri demi mengajaknya kembali seperti sedia kala. Aku tak punya cukup kata untuk menjelaskannya, maka aku akan merekonstruksi penggalan esai Yulden Erwin ini: “Aku betapa ingin mengajak diriku untuk keluar dari sebuah situasi batas – keputusasaan, fase depresif, atau pahitnya nasib, atau, mungkin juga, kematian. Situasi itulah yang menjadi latar sugestif yang memecah diriku ke dalam aku-lirik, aku-objek, maupun aku-pembaca di dalam puisi-puisi”.
Aku percaya ada sesuatu di dunia ini yang mampu menggantikan kertas-kertas usang tentang konflik psikologis yang selama berbulan-bulan ini bertumpuk tak beraturan dalam kepalaku. Dan aku percaya, “sesuatu” tersebut adalah kata-kata dalam sebuah puisi.
Bandung, 8 November 2021
[1] Kutipan di awal tulisan adalah bagian dari puisi Aan Mansyur, Self Help Poem. Dimuat pada hurufkecil.substack.com, 26 Maret 2021. [2] Fauzi Sukri, Bahasa Ruang, Ruang Puitik, Yogyakarta: Basabasi, 2018, hal. 69. [3] Kutipan tersebut diambil dari puisi Subagio Sastrowardoyo, “Sajak”. Dimuat dalam buku Dan Kematian Makin Akrab (Grasindo, 1995). [4] Nugraha Arif, Terapi Puisi: Dasar-dasar Penggunaan Puisi sebagai Modalitas dalam Psikoterapi, dimuat di Jurnal Wacana Vol. 4. No. 8, 2012. [5] Ibid.




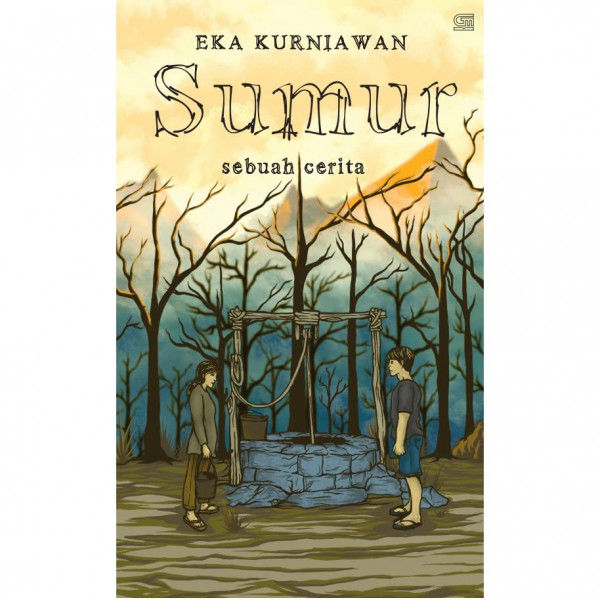

Comments